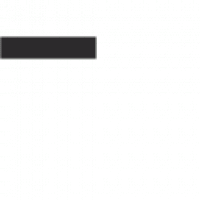DI BALIK KELIR: KISAH ELISHA ORCARUS ALLASSO
Siapa tidak mengenal Elisha Orcarus Allasso, sindhèn kocak yang sering tampil dalam pertunjukan wayang Ki Seno Nugroho.

GARIS HIDUP: KISAH DI BALIK LAYAR SETIYOKO, PERUPA MUDA ASAL SUKOHARJO
Tepatnya kemarin sore, kami berencana akan melihat pameran di galeri milik seniman Ugo Untoro. Pertama

“PESAN PANDEMI” DINA TRIASTUTI
Sore itu, saya berkunjung ke rumah kontrakan Dina Triastuti, manajer Kalanari Theatre Movement. Di tengah

Sholawat Kaliopak (lirik)
لَااَلَهَ اِلَّا الله # اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْن مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله # صَدِقُ الْوَعْدِالْاَمِن Laa ilaaha